SURVEI HIDROGRAFI PESISIR PANTAI
DAN PERAIRAN SUNGAI DUA LAUT KABUPATEN TANAH BUMBU
LAPORAN PRAKTEK
SURVEI HIDROGRAFI
Linda
Apriliani
1610716120003
PROGRAM
STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS
PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
BANJARBARU
2020
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Survei hidrografi adalah suatu ilmu pengukuran, menguraikan, dan mengembangkan tentang sifat-sifat dan konfigurasi dasar laut yang dihasilkan oleh kegiatan survei bathimetri, geologi dan geofisika. Selain itu juga menguraikan hubungan geografis antara laut dengan daratan terdekat yang dihasilkan dengan kegiatan positioning garis pantai serta menguraikan sifat dan dinamika air laut, yang dihasilkan lewat pengukuran/pengamatan pasang surut, arus laut, gelombang dan sifat fisik air laut.
Menurut IHO (International Hydrographic Organization) survei hidrografi adalah kegiatan pengukuran dan pengumpulan data untuk memperoleh gambar permukaan dasar laut, kondisi dan sumberdaya suatu wilayah laut yang kemudian diolah, dievaluasi dan disajikan dalam bentuk buku, peta laut serta informasi mengenai kelautan lainnya yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pertahanan keamanan suatu negara sehingga dalam kegiatan survei hidrografi perlu adanya perencanaan yang baik dan terstruktur.
Data terkait fenomena perairan dan dinamika badan air dapat diperoleh melalui kegiatan survei hidrografi. Data yang dihasilkan tersebut akan menjadi informasi geospasial dan informasi awal untuk menggambarkan kondisi perairan. Dalam kegiatannya, survei hidrografi memiliki beberapa aktivitas utama diantaranya pengukuran detail dan situasi garis pantai, pengamatan pasang surut, pengukuran kedalaman atau pemeruman dan penggunaan sistem referensi.
Sungai Dua Laut merupakan salah satu wilayah yang unik dengan karakteristik pantai berpasirnya yang landai serta memiliki 2 sungai yang bermuara ke laut tentunya akan mempengaruhi dinamika pesisir yang berpengaruh terhadap kondisi perairan. Adanya potensi ekologi yang besar seperti mangrove, terumbu karang dan lamun membuat wilayah ini sangat potensial jika dijadikan sebagai daerah wisata baik wisata pantai maupun wisata bahari. Maka dari itu diperlukan kegiatan survei hidrografi untuk melihat gambaran dan kondisi lautnya yang harapannya dapat dijadikan sebagai informasi awal terkait kondisi perairannya serta nantinya dapat menjadi acuan dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan terkait wilayah tersebut.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penulisan
laporan ini adalah sebagai berikut:
1.
Untuk menentukan karakteristik pasang surut
berdasarkan data pengukuran pasut di suatu wilayah perairan Sungai Dua Laut.
2.
Untuk
menentukan lokasi titik sampling,
peralatan dan analisis data.
3.
Untuk memetakan dan pengukuran garis pantai. yang sesuai dengan peralatan yang tersedia dan kondisi lapangan.
4.
Untuk
memetakan kedalamam terkoreksi sesuai
metoda dan peralatan perum yang dipilih.
5.
Untuk dapat membuat peta laut sesuai kaidah
kartografi.
1.3. Ruang Lingkup
1.3.1. Ruang Lingkup Lokasi
Ruang lingkup lokasi praktikum lapang kali
ini bertempat di perairan Sungai Dua
Laut, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Lokasi perairan yang diteliti berada sekitar 0,5 - 4 mil dari pantai dengan lebar lintasan sepanjang ±4 km.
1.3.2. Ruang
Lingkup Materi
Ruang lingkup materi pada praktikum
lapang kali ini adalah sebagai berikut:
1.
Analisis hidro-oseanografi meliputi pasang surut, garis pantai, substrat dasar
dan kedalaman perairan.
2.
Pembuatan peta laut
BAB
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Survei Hidrografi
Survei adalah kegiatan terpenting dalam
menghasilkan informasi hidrografi, seperti: penetuan posisi laut dan
penggungaan sistem referensi, pengukuran kedalaman, pengukuran arus, pengukuran
sedimen, pengamatan pasut, pengukuran detil situasi dan garis pantai (Eka
Djunasjah, 2005).
Menurut Dirjen Perhubungan Laut (2018)
survei hidrografi adalah kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengamatan yang
dilakukan di wilayah perairan dan sekitar pantai untuk menggambarkan sebagian
atau keseluruhan permukaan bumi, terutama yang digenangi oleh air, pada suatu
bidang datar (kertas peta) yang disajikan dalam bentuk informasi titik-titik
kedalaman, garis kontur kedalaman dan titik-titik tinggi serta berbagai
keragaman diatas dan dibawah permukaan laut.
Pada prinsipnya pekerjaan hidrografi
merupakan pekerjaan lanjutan dari pekerjaan survei topografi di darat yang
pelaksanaannya dilakukan di permukaan laut. Seiring dengan perkembangan
teknologi kelautan, pekerjaan hidrografi tidak lagi terbatas hanya untuk
navigasi pelayaran saja, tetapi juga untuk kebutuhan ilmu dan teknologi
kelautan seperti ekplorasi kelautan, perikanan, energi laut, perlindungan lingkungan
laut, tata ruang laut, rekayasa bangunan pantai dan lepas pantai, klimatologi,
serta pertanan dan keamanan. Data dan informasi yang dihasilkan bukan hanya
peta laut saja, tetapi juga informasi lain seperti geologi dasar laut yang
digunakan untuk penelitian kandungan minyak bumi, karakteristik massa air
diperlukan dalam studi iklim dan untuk kepentingan militer bawah air (kapal
selam dan ranjau), pola arus dalam penelitian perikanan dan atau pencemaran
laut dan lain sebagainya (Harsono dan Hartoyo, 2018).
2.2. Pasang Surut
Pasang-surut (pasut) merupakan salah
satu gejala alam yang tampak nyata di laut, yakni suatu gerakan vertikal (naik
turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang) dari seluruh partikel
massa air laut dari permukaan sampai bagian terdalam dari dasar laut. Gerakan
tersebut disebabkan oleh pengaruh gravitasi (gaya tarik menarik) antara bumi
dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan matahari (Surinarti,
2007).
Gaya pembangkit
pasang-surut merupakan hasil penjumlahan gaya-gaya yang disebabkan oleh gaya
gravitasi dan gaya centrifugal. Bila bumi tidak berotasi dalam melakukan
revolusinya maka besar gaya centrifugal di setiap titik pada permukaan bumi
adalah sama, namun besaran gaya gravitasi tidak sama sehingga intensitas dan
arah gaya pembangkit pasang surut di permukaan bumi bervariasi. Komponen
menegak terhadap gaya gravitasi lebih kecil dari komponen mendatar. Komponen
yang mendatar ini menghasilkan arus dan variasi tinggi muka laut di permukaan
bumi (Baharuddin, 2017).
Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI)
Tahun 2010 mengenai pengamatan pasang surut pada kegiatan survei hidrografi
bertujuan untuk menentukan bidang acuan kedalaman (muka air laut rerata, muka
surutan) serta menentukan koreksi hasil pemeruman. Dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Dilaksanakan
dengan menggunakan palem atau tide gauge yang lain.
b. Pengamatan
mencakup area survei batimetri dan jumlah stasiun pasang surut harus
mempertimbangkan karakteristik pasang surut asurvei.
c. Untuk keperluan
analisa dan peramalan lama pengamatan tidak boleh kurang dari 29 hari dengan
interval pengamatan maksimal 30 menit, jika perubahan ketinggian air berjalan
dengan cepat dan amplitudo airnya besar, interval pengamatan dapat
ditingkatkan. Interval pembacaan juga dapat ditingkatkan tiap 15 menit pada
saat menuju pasang tertinggi atau surut terendah.
d. Untuk keperluan
reduksi data pemeruman, pengamatan dilakukan selama pemeruman berlangsung.
e. Satuan
pengukuran dalam cm. dengan total kesalahan pengukuran tidak melebihi lima cm
untuk orde khusus dan tidak melebihi 10 cm untuk orde yang lain pada tingkat
kepercayaan 95%.
f. Bidang acuan
tinggi muka laut harus diikatkan pada benchmark terdekat dengan leveling orde
dua.
g. Untuk keperluan
koreksi kedalaman dibuat co-tidal charts daerah survei.
h. Konstanta pasut
dihitung dengan menggunakan metode admiralty atau perataan kuadrat terkecil (least square adjustment).
Gambar
1. Pengamatan Pasang surut
2.3. Garis Pantai
Garis pantai merupakan batas
pertemuan antara daratan dengan bagian laut saat terjadi air laut pasang
tertinggi. Garis ini bisa berubah karena beberapa hal seperti abrasi dan
sedimentasi yang terjadi di pantai, pengikisan ini akan menyebabkan
berkurangnya areal daratan, sehingga menyebabkan berubahnya garis pantai
(Triadmojo, 1999). Garis yang menggambarkan pertemuan antara perairan dan
daratan di wilayah pantai pada saat kedudukan pasang tertinggi ,penentuan garis
pantai di daerah rawa dan bakau adalah tepi luar dari wilayah tumbuhan (SNI, 2010).
Perubahan terhadap garis pantai
adalah satu proses tanpa henti (terus menerus) melalui pelbagai proses baik
pengikisan (abrasi) maupun penambahan (akresi) pantai yang diakibatkan oleh
pergerakan sedimen, arus susur pantai (longshore
current), tindakan ombak dan penggunaan tanah (Vreugdenhil1999). Perubahan
pada garis pantai yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut di atas dapat
menunjukkan kecenderungan perubahan garis
pantai tersebut terkikis mengarah ke daratan atau bertambah dalam hal ini
menjorok ke laut (Arief dkk, 2011).
Menurut Badan Informasi Geospasial
(BIG) Tahun 2014 ada beberapa metode yang digunakan dalam kegiatan survei
hidrografi diantaranya persiapan, studi pustaka, pengukuran dan analisis hasil.
Metode tersebut adalah sebagai berikut:
1. Persiapan
Persiapan tersebut meliputi
persiapan teknis, yaitu pengecekan kelengkapan dan kelayakan alat survey serta
persiapan non teknis yang meliputi administrasi, pembagian personil/tim
lapangan dan tim pengolahan, persiapan formulir pengukuran, pembahasan dana
survey dan pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Studi Pustaka
a.
Titik
Kontrol.
Metode Pelaksanaan pengukuran titik
kontrol horizontal dalam pekerjaan survey hidrografi mengikuti SNI No.
19-6724-2002 tentang jaring kontrol horizontal. Titik kontrol tersebut
merupakan titik yang nilai posisinya terikat dalam koordinat nasional pada
titik tetap BIG yang menggunakan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI)
2013. Penentuan lokasi titik kontrol dilakukan diatas peta kerja yang ada
kemudian dicek keberadaan titiknya di lapangan.
b.
Metode
Pengukuran
Pengukuran titik
kontrol menggunakan metode Static Relative Positioning dengan pengematan
Difference Carrier Beat Phase yaitu pengamatan dengan menghitung panjang
vektor baseline. Pada pengukuran ini receiver mengamati data
selama 180 menit dan minimum menangkan 6 sinyal satelit dengan epoch 15
detik. Pedoman waktu pengamatan untuk alat jenis single frekuensi dan dual frekuensi
sesuai dengan tabel 1.
Tabel
1. Pedoman waktu pengamatan untuk alat jenis single frekuensi dan
dual frekuensi
Panjang Baseline (km)
|
Teknik
|
Minimum/L1 (menit)
|
Minimum L1+L2 (menit)
|
0 – 5
|
Statik
|
30
|
15
|
5 -10
|
Statik
|
50
|
25
|
10 -30
|
Statik
|
90
|
60
|
30 -50
|
Statik
|
180
|
120
|
Hingga kini pengukuran teristris masih dilakukan,
seperti untuk pengukuran garis pantai karena tidak memungkinkan sebuah kapal
dapat menjangkau kedalaman tertentu. Terdapat 2 metode yang digunakan untuk
melakukan pengukuran garis pantai. Kedua metode ini hanya dibedakan berdasarkan
tipe alat yang digunakan, yakni pengukuran dengan metode GPS RTK dan metode
pengukuran dengan rambu penduga.
a.
Pengamatan
Pasang Surut (pasut)
Frekuensi terjadinya pasut di suatu
wilayah, menunjukan tipe pasut di wilayah tersebut. Ada 4 jenis pasut secara
umum, yakni; pasut harian ganda (semidiurnal
tide), pasut harian tunggal (diurnal
tide), pasut campuran condong ke harian tunggal (mixed tide prevailing diurnal), pasut campuran condong ke haian
ganda (mixed tide prevailing semidiurnal).
Fenomena ini tentunya mempengaruhi
posisi garis pantai, sehingga dalam hal ini memperhitungkan nilai tunggang
pasut yakni nilai jarak vertkal yang dihitung dari kedudukan permukaan air
tertinggi dan kedudukan air terendah (Poerbandono dan Djurnarsjah, 2005).
b. Pengukuran Garis Pantai
i.
Metode
Tongkat Penduga
Tongkat
penduga/rambu ukur adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur
ketinggian suatu tempat. Dalam pekerjaan survey garis pantai, ketinggian dibaca
berdasarkan batas air yang menempel pada rambu. Metode pengukuran garis pantai
dengan menggunakan tongkat penduga dilengkapi dengan GPS handheld. GPS
ini berfungsi untuk mengetahui koordinat posisi titik pengamatan, sedangkan
rambu ukur digunakan untuk menghitung ketinggian permukaan air.
ii.
Metode
GPS RTK
Pengukuran dengan metode ini
menggunakan GPS RTK Trimble R4 ( Base dan Rouver ).Prinsip dasar penentuan
posisi dengan GPS seperti halnya pengukuran pemotongan ke muka pada survey
konvensional.Pengukuran dengan GPS yang diukur adalah jarak antara receiver
dengan sekurang-kurangnya 3 satelit agar dapat mengetahui posisi pada stasiun
pengamatan.Jarak tersebut tidak dapat diukur secara langsung, tetapi diukur
dengan menghitung waktu rambat sinyal dari satelit ke stasiun pengamat atau
jumlah fase gelombang sinyal yakni fungsi waktu rambat sinyal.Pada metode RTK
kedua receiver harus ada hubungan telekomunikasi secara langsung dan kontinyu.
Pada kajian ini metode RTK yang digunakan adalah metode kinematik absolute,
dimana satu receiver dijadikan sebagai base yang sudah diketahui posisinya
kemudian dihubungkan dengan radio terhadap receiver lainnya. Kemudian receiver
yang telah dihubungkan dengan base bisa digunakan untuk mendapatlkan nilai
ketinggian dan nilai koordinat posisi titik pengamatan.
1. Pengukuran
a. Metode RTK
Survei ini dilakukan untuk
menentukan titik posisi (X, Y, Z) yang mana posisi Z nya ini ditentukan dari
tiga titik yang mempunyai nilai elevasi mendekati >= 1,40 m, kemudian nilai
elevasi yang mendekati 0,70 m, dan nilai
elevasi <= 0 m dihitung dari Chart Datum .
Ketinggian 1,39 m didapat dari tinggi tunggang yang diketahui.
b. Tongkat Penduga
Posisi pengamatan yang diambil sama
halnya dengan posisi pengamatan dengan menggunakan metode RTK yakni pada
ketinggian >= 1,39 meter; 0,7 meter; 0 meter. Pengukuran menggunakan tongkat
penduga dilengkapi dengan GPS handheld untuk mengetahui posisi X dan Y pada
tiap-tiap titik pengamatan.
Gambar
2. Pengukuran kedalaman dengan rambu ukur/tongkat penduga
2.4. Kedalaman
Pemeruman
adalah proses dan aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh gambaran (model)
bentuk permukaan (topografi) dasar perairan (seabed surface). Proses
penggambaran dasar perairan tersebut (sejak pengukuran, pengolahan hingga
visualisasi) disebut dengan survei batimetri. Model batimetri (kontur
kedalaman) diperoleh dengan menginterpolasikan titi-titik pengukuran kedalaman
bergantung pada skala model yang hendak dibuat (Hidayat dkk, 2014).
Pemeruman dilakukan dengan
membuat profil (potongan) pengukuran kedalaman. Lajur perum dapat berbentuk
garis-garis lurus, lingkaran-lingkaran konsentrik, atau lainnya sesuai metode
yang digunakan untuk penentuan posisi titik-titik fiks perumnya. Lajur-lajur
perum didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan pendeteksian perubahan
kedalaman yang lebih ekstrem. Untuk itu, desain lajur-lajur perum harus
memperhatikan kecenderungan bentuk dan topografi pantai sekitar perairan yang
akan disurvei. Agar mampu mendeteksi perubahan kedalaman yang lebih ekstrem
lajur perum dipilih dengan arah yang tegak lurus terhadap kecenderungan arah
garis pantai (Kusuma, 2014).
Gambar
3. Titik pemeruman
Sistem
batimetri dengan menggunakan singlebeam secara umum mempunyai susunan
transceiver (tranducer/reciever) yang terpasang pada lambung kapal atau sisi
bantalan pada kapal. Sistem ini mengukur kedalaman air secara langsung dari
kapal penyelidikan. Transciever yang terpasang pada lambung kapal mengirimkan
pulsa akustik dengan frekuensi tinggi yang terkandung dalam beam (gelombang
suara) secara langsung menyusuri bawah kolom air. Energi akustik memantulkan
sampai dasar laut dari kapal dan diterima kembali oleh tranceiver seperti pada
gambar 3.4. Transceiver terdiri dari sebuah transmitter yang mempunyai fungsi
sebagai pengontrol panjang gelombang pulsa yang dipancarkan dan menyediakan
tenaga elektrik untuk frekuensi yang diberikan.
Gambar 4. Singlebeam
echosounder
Transmitter
ini menerima secara berulang-ulang dalam kecepatan yang tinggi, sampai pada
orde kecepatan milisekon. Perekaman kedalaman air secara berkesinambungan dari
bawah kapal menghasilkan ukuran kedalaman beresolusi tinggi sepanjang lajur
yang disurvei. Informasi tambahan seperti heave (gerakan naikturunnya kapal
yang disebabkan oleh gaya pengaruh air laut), pitch (gerakan kapal ke arah
depan (mengangguk) berpusat di titik tengah kapal), dan roll (gerakan kapal ke
arah sisi-sisinya (lambung kapal) atau pada sumbu memanjang) dari sebuah kapal
dapat diukur oleh sebuah alat dengan nama Motion
Reference Unit (MRU), yang juga digunakan untuk koreksi posisi pengukuran
kedalaman selama proses berlangsung.
Gambar 5. Pengukuran sounding dengan
sonar
2.5. Substrat Dasar
Menurut Maulana
(2010) sedimen yang di jumpai di dasar lautan dapat berasal dari beberapa
sumber yang dibedakan menjadi empat
yaitu :
a.
Lithougenus sedimen yaitu
sedimen yang berasal dari erosi pantai dan material hasil erosi daerah up land.
Material ini dapat sampai ke dasar laut melalui proses mekanik, yaitu
tertransport oleh arus sungai dan atau arus laut dan akan terendapkan jika
energi tertrransforkan telah melemah.
b.
Biogeneuos sedimen yaitu
sedimen yang bersumber dari sisa-sisa organisme yang hidup seperti cangkang dan
rangka biota laut serta bahan-bahan organik yang mengalami dekomposisi.
c.
Hidreogenous sedimen yaitu
sedimen yang terbentuk karena adanya reaksi kimia di dalam air laut dan
membentuk partikel yang tidak larut dalam air laut sehingga akan tenggelam ke
dasar laut, sebagai contoh dan sedimen jenis ini adalah magnetit, phosphorit
dan glaukonit.
Cosmogerous sedimen yaitu sedimen yang bersal dari berbagai
sumber dan masuk ke laut melalui jalur media udara/angin. Sedimen jenis ini dapat
bersumber dari luar angkasa, aktifitas gunung api atau berbagai partikel darat
yang terbawa angin. Material yang bersal dari luar angkasa merupakan sisa-sisa
meteorik yang meledak di atmosfir dan jatuh di laut. Sedimen yang bersal dari
letusan gunung berapi dapat berukuran halus berupa debu volkanin, atau berupa
fragmen-fragmen aglomerat. Sedangkan sedimen yang bersal dari partikel di darat
dan terbawa angin banyak terjadi pada daerah kering dimana proses
eolian dominan namun demikian dapat juga terjadi pada daerah sub tropis saat
musim kering dan angin bertiup kuat. Dalam hal ini umumnya sedimen tidak dalam
jumlah yang dominan dibandingkan sumber-sumber yang lain.
Dyer (1986) menyatakan bahwa sedimen
dengan ukuran yang lebih halus lebih mudah berpindah dan cenderung lebih cepat
daripada ukuran kasar. Fraksi halus terangkut dalam bentuk suspensi sedangkan
fraksi kasar terangkut pada dekat dasar laut. Selanjutnya partikel yang lebih
besar akan tenggelam lebih cepat daripada yang berukuran kecil. Berdasarkan
sumbernya Barnes (1969) membagi jenis sedimen, yakni sedimen yang bersumber
dari limpasan sungai yang jenisnya banyak mempengaruhi pembentukan morfologi
pantai di sekitar muara sungai (sedimen
of inlets) dan sedimen yang bersumber dari darat yang terangkut ke laut
oleh angin dan drainase atau penguraian sisa-sisa organisme (pyroclastic sediment). Sedimen
berdasarkan ukuran butirnya dapat diklasifikasikan yakni lempung, lanau, pasir,
kerikil, koral (pebble), cobble, dan batu (boulder).
2.6. Peta Laut
Peta laut atau dikenal dengan
istilah Nautical Chart merupakan peta yang dirancang secara spesifik untuk
memenuhi kebutuhan navigasi laut dengan menampilkan (Haas, 1986 dalam Abdillah):
1.
Kedalaman
laut dan fisiografi dasar laut khususnya memperhatikan bahayabahaya navigasi.
2.
Bentuk
dasar dan tingkatan dari bentuk pantai serta bentuk dasar laut.
3.
Variasi
bentuk keselamatan navigasi.
4.
Fitur-fitur
laut dan beberapa detail topografi yang bermanfaat untuk navigasi laut.
Fungsi utama dari peta laut adalah
menyampaikan informasi terkait wilayah laut dan pesisir serta
perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya untuk kebutuhan: 1. Keselamatan,
efektivitas, dan efisiensi bidang navigasi.
2.
Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut.
3.
Pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir.
4.
Perlindungan lingkungan laut.
5.
Pertahanan maritim.
Secara khusus untuk peta navigasi laut,
informasi utama yang harus dikomunikasikan terdiri atas (Poerbandono, 1998):
1.
Kedalaman perairan dengan pokok perhatian pada bahaya navigasi (kedangkalan,
bangkai kapal tenggelam, daerah latihan militer, dan sebagainya).
2.
Sifat dan jenis garis pantai serta sifat material dasar laut dibawahnya.
3.
Posisi, jenis, dan karakter sarana bantu navigasi pelayaran.
4.
Bentuk atau unsur topografi khusus yang dapat dipakai untuk sarana bantu
navigasi.
3.1. Waktu dan
Lokasi
Penelitian
ini dilaksanakan selama 1 bulan yang dimulai pada November hingga Desember
2019. Rentang waktu tersebut meliputi pengambilan data lapangan yaitu pada
tanggal 25 – 28 November 2019, analisis sampel selama ±20 hari dan pengerjaan
laporan. Lokasi penelitian bertempat di pesisir Sungai Dua Laut, Kecamatan
Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang terlihat pada gambar 6. Analisis sampel dan pengolahan data dilakukan di Laboratorium
Oseanografi Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Unversitas
Lambung Mangkurat.
3.2. Alat dan Bahan
3.2.1. Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian
kali ini adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Alat yang
digunakan
No.
|
Nama
|
Kegunaan
|
1.
|
GPS Mapsounder
|
Untuk mengukur kedalaman
perairan
secara otomatis
|
2.
|
Kapal
|
Untuk transportasi ke lokasi
sampling
|
3.
|
Hand GPS
|
Untuk menandai posisi
pengukuran
data
|
4.
|
Theodolite
|
Untuk melakukan pengukuran
garis pantai
|
5.
|
Waterpass
|
Untuk melakukan pengukuran
garis pantai
|
6.
|
Tiang Pasut
|
Untuk mengukur tinggi muka air
laut
|
3.3. Metode Perolehan Data
3.3.1. Penentuan Titik Sampling
Penentuan titik sampling dilakukan
sebelum turun ke lapangan dengan menentukan titik sebaran pada peta kerja
berdasarkan citra satelit di daerah pesisir Sungai Dua Laut. Titik sampling
ditentukan dengan metode purposive
sampling artinya pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Saat pengambilan sampel di lapangan, catat
waktu pengambilan dan koordinat titik sampling menggunakan hand GPS sebagai data GCP.
3.3.2. Garis Pantai
Pengamatan dan pengukuran garis
pantai dilakukan dengan menggunakan alat waterpass
dan theodolite sepanjang garis
pantai yang sudah ditentukan dan menandai titik pengamatan menggunakan hand GPS.
3.3.3. Pasang Surut
Menempatkan
(pemasangan) rambu pasut pada tempat yang aman, mudah dibaca dan tidak
bergerak-gerak akibat arus atau gelombang. Pemasangan nol rambu terletak di
bawah permukaan air pada saat air rendah saat surut besar dan bacaan skala
masih terbaca pada saat terjadi air tinggi saat pasang besar. Metode
pengamatannya dilakukan dengan pembacaan secara langsung dan dicatat secara
kontinyu setiap 30 menit selama masa survei berlangsung.
3.3.4. Substrat Dasar Perairan
Pengambilan sampel substrat dasar
menggunakan grab sampler yang
diletakkan pada 24 stasiun sesuai peta kerja, lalu mencatat koordinat posisi
dimana substrat diambil dengan menggunakan GPS. Sampel yang telah didapatkan
dianalisis secara megaskopis dan beberapa sampel disimpan kedalam kantung
sampel untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium dengan menggunakan metode
granulometri.
3.3.5. Kedalaman
Pengukuran kedalaman yang dilakukan
menggunakan GPS mapsounder yang
dipasang pada kapal. Setelah peralatan survei kedalaman dipasang pada kapal,
kapal akan berjalan sesuai lajur yang telah ditentukan pada GPS mapsounder sehingga secara otomatis kedalaman
akan terekam pada alat tersebut.
3.3.6. Pemetaan Garis Pantai
Pemetaan garis pantai dilakukan
dengan menggunakan alat waterpass dan
theodolite sepanjang garis pantai
yang sudah ditentukan dan menandai titik pengamatan menggunakan hand GPS.
3.3.7. Kelerengan dan Geomorfologi Pantai
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan
alat waterpass dan theodolite ke arah laut dan darat yang bersesuaian
dengan pengukuran pantai. Mengamati dan mencatat kenampakan alam di pantai saat
melakukan pengukuran.
3.3.8. Citra Satelit
Data yang digunakan adalah data citra satelit Landsat 8 yang diperoleh
dari Science for a Changing World pada
situs https://earthexplorer.usgs.gov/ dan Google Earth Pro.
3.4. Metode Analisis Data
3.4.1. Garis Pantai
Perhitungan garis pantai dapat
dihitung dengan persamaan sebagai berikut:
dimana:
∆H =
Beda tinggi
Ba =
Bacaan benang atas
Bb =
Bacaan benang bawah
m =
kelerengan
ta =
tinggi alat
Bt =
Bacaan benang tengah
Ketinggian bench mark terhadap MSL dapat dihitung menggunakan persamaan
sebagai berikut:
HBM = Tinggi BM
∆H =
Beda tinggi
MSL = Tinggi muka air laut rata-rata
3.4.2. Pasang Surut
Perhitungan untuk tipe pasang surut
berdasarkan kriteria Courtier untuk memperoleh bilangan Formzal (F) yang dinyatakan dalam bentuk:
dimana:
dengan
ketentuan :
F ≤ 0,25 =
Pasang surut tipe ganda (semidiurnal)
0,25 < F ≤1,5 = Pasang surut tipe campuran condong keharian
ganda (mixed tide prevailing semidiurnal)
1,5 < F ≤
3,0 = Pasang surut tipe campuran condong
keharian tunggal (mixed tide prevailing diurnal)
F > 3.0 =
Pasang surut tipe tunggal (diurnal)
3.4.3. Substrat Dasar Perairan
a.
Analisis
Ukuran Butir
Analisis data sedimen dengan metode
megaskopis adalah dengan mengidentifikasi secara umum jenis sampel sedimen yang
diperoleh dari lokasi penelitian. Prosedur
kerja metode ini adalah sebagai berikut :
1.
Sampel
sedimen yang diperoleh di lapangan dikumpulkan sesuai dengan lokasi
masing-masing sampel, kemudian dijemur dan dioven sampai kering, setelah itu di
masukkan ke dalam
gelas ukur.
2.
Sedimen
kering tersebut diambil dan kemudian ditimbang untuk dianalisa seberat 100 gr
sebagai berat awal.
3.
Sampel
dimasukkan ke dalam ayakan untuk diguncang melalui mesin pengguncang saringan
atau secara manual, sehingga didapatkan pemisahan ukuran masing-masing partikel
sedimen berdasarkan ukuran ayakan.
4.
Sampel
dipisahkan dari ayakan (untuk antisipasi tertinggalnya butiran pada ayakan
disikat dengan perlahan). Hasilnya kembali ditimbang untuk mendapatkan berapa gram hasil masing-masing
tiap ukuran ayakan.
5.
Untuk
perhitungan data ukuran butir sedimen menggunakan software gradistat.
b.
Transport
Sedimen
Besar transport sedimen akibat gelombang
dapat dihitung melalui persamaan fluks energi sebagai berikut:
keterangan:
rs =
Massa jenis sedimen
r
= Massa jenis air laut
gb =
Indeks gelombang pecah
n = Porositas sedimen
ab = Sudut gelombang
pecah
Hasil pengukuran volume
masing-masing stasiun sedimen trap selanjutnya dihitung volume transport
sedimennya, dengan menggunakan persamaan berikut:
keterangan:
Qx =
volume transport sedimen sejajar pantai
Qy =
volume transport sedimen tegak lurus pantai
Vu =
volume sedimen arah utara pada sedimen
trap
Vs =
volume sedimen arah selatan pada sedimen
trap
Vt =
volume sedimen arah timur pada sediment
trap
Vb =
volume sedimen arah barat pada sediment
trap
Perhitungan arah transpor sedimen dapat
menggunakan persamaan sebagai berikut:
keterangan:
Arc tg =
arah transpor sedimen
Qx =
volume transport sedimen sejajar pantai
Qy =
volume transport sedimen tegak lurus pantai
Perhitungan resultan transpor
sedimen dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:
keterangan:
r =
arah transpor sedimen
Qx =
volume transport sedimen sejajar pantai
Qy =
volume transport sedimen tegak lurus pantai
3.4.4. Koreksi Garis Pantai dan Kedalaman
Koreksi kedalaman perairan dilakukan
dengan memperhitungkan nilai kedalaman hasil pengukuran lapangan, ketinggian
muka laut saat melakukan pengukuran dan nilai ketinggian muka laut rata-rata
(MSL). Koreksi kedalaman perairan menggunakan persamaan berikut mengacu pada
USACE (2003) sebagai berikut:
dimana:
∆d =
kedalaman perairan terkoreksi (m)
dt =
kedalaman perairan yang diukur pada waktu t (m)
ht = ketinggian muka laut pada waktu t (m)
MSL =
ketinggian muka laut rata-rata (m)
3.4.5. Kelerengan dan Geomorfolgi
Kemiringan pantai (kelerengan) dihitung
menggunakan persamaan berikut mengacu pada USACE (2003) sebagai berikut:
dimana:
tan β =
kemiringan pantai (°)
d =
kedalaman perairan (m)
m =
jarak dari garis pantai hingga kedalaman d
(m)
Jarak pergeseran garis pantai hasil
koreksi terhadap MSL dihitung menggunakan persamaan berikut:
dimana:
ɳ =
posisi muka air saat perekaman citra
x =
jarak pergeseran garis pantai hasil koreksi
tan β =
kemiringan pantai (°)
3.4.6. Pembuatan Peta Laut
Peta sebaran sedimen dan kedalaman laut di wilayah studi yaitu dapat
dilakukan dengan menggunakan
aplikasi Surfer 15 dan/atau Arcgis 10.7 menggunakan metode krigging
agar mendapatkan sebaran spasial. Sebaran spasial tersebut menggambarkan keadaan sebaran sedimen dan
kedalaman di lokasi studi.
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pasang
Surut
Pasang-surut
(pasut) merupakan salah satu gejala alam yang tampak nyata di laut, yakni suatu
gerakan vertikal (naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang)
dari seluruh partikel massa air laut dari permukaan sampai bagian terdalam dari
dasar laut. Gerakan tersebut disebabkan oleh pengaruh gravitasi (gaya tarik
menarik) antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan
matahari (Surinarti, 2007). Pasang surut memiliki tiga tipe yakni pasang surut
harian tunggal (diurnal tides), tipe
harian ganda (semi diurnal tides)
jika terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari dan tipe campuran
(mixed tides). Tipe pasang surut
campuran dibagi menjadi dua bagian yaitu tipe campuran dominasi ganda dan tipe
campuran dominasi tunggal. Grafik pasang surut Perairan Sungai Dua Laut
disajikan pada Gambar 7.
Gambar 7. Grafik
perbandingan pasang surut hasil pengukuran dan prediksi terhadap MSL
Berdasarkan
grafik diatas dapat diketahui bahwa tipe pasang surut di Perairan Sungai Dua
Laut yaitu campuran condong ke harian ganda, hal ini terlihat dari grafik bahwa
ada dua kali pasang dan dua kali surut namun memiliki tinggi muka air yang
berbeda. Pasang surut tertinggi terjadi pada tanggal 27 November 2019 dengan
nilai sebesar 217 cm di dapatkan dari hasil pengukuran lapangan. Pasang
tertinggi terjadi pada pukul 18:30 – 20:30 WITA sedangkan pada prediksi terjadi
pada jam 20.00 – 22.00 WITA. Surut terendah memiliki tinggi sebesar 154 cm yang
terjadi pada tanggal 26 November 2019 pukul 12:30 – 14:30 WITA sedangkan
menurut prediksi terjadi di jam 04.30 – 6.00 WITA.
Pada Gambar 7 terlihat perbedaan yang
cukup signifikan antara hasil pengukuran dengan analisis admiralty. Pola
pergerakan pasang surut di wilayah ini memiliki pola yang hampir sama namun
memiliki nilai tinggi muka air yang
berbeda.
Data prediksi pasang surut yang didapatkan
dari Mike ToolBox dianalisis
menggunakan metode admiralty dan
menghasilkan konstanta harmonik pasang hurut sebagai mana disajikan pada Tabel
2.
Tabel 2. Konstanta harmonik pasang surut
Komponen Pasut
|
So
|
M2
|
S2
|
N2
|
K1
|
O1
|
M4
|
MS4
|
K2
|
P1
|
A cm
|
170,3
|
32,7
|
51,2
|
8,8
|
40,3
|
36,7
|
0,7
|
0,8
|
13,8
|
13,3
|
g°
|
268,8
|
234,3
|
161,9
|
223,1
|
178,3
|
137,3
|
323,3
|
234,3
|
223,1
|
4.1.
Garis
Pantai
Garis pantai di
Perairan Sungai Dua Laut dianalisis dengan menggunakan citrsa sentinel yang
memiliki perbedaan yang cukup jauh. Analisis garis pantai menggunakan
perhitungan saat berada pada MSL, HAT
dan LAT. Pemetaan garis pantai pada saat MSL, LAT dan HAT disajikan pada Gambar
8.
Gambar 8. Garis pantai terhadap MSL, LAT
dan HAT
Pada
Gambar 8. garis berwarna hitam merupakan garis pantai pada saat muka air laut
surut terendah (LAT), garis berwarna kuning merupakan garis pantai pada saat
keadaan air laut pasang tertinggi (HAT), dan untuk garis biru merupakan garis
pantai pada saat muka air laut rata-rata (MSL). Terlihat pada gambar tersebut
bahwa MSL dan LAT memiliki perbedaan yang cukup jauh antara MSL, HAT dan LAT.
4.1.
Kedalaman
Pemeruman
merupakan salah satu kegiatan survey hidrografi untuk mendapatkan kontur
topografi dasar laut dengan bantuan alat salah satunya GPS Mapsounder. Kontur topografi ini menggambarkan bentuk dasar
laut yang beragam. Hasil dari pemeruman dapat digambarkan dalam bentuk 2 dimensi
maupun 3 dimensi. Berdasarkan pemeruman yang dilakukan di perairan Sungai Dua
Laut di dapatkan kedalaman maksimal sebesar 7,5 meter yang berada pada wilayah
tenggara. Untuk lebih jelaskan dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Kontur kedalaman Perairan
Sungai Dua Laut
Berdasarkan Gambar
9 kontur kedalaman di Perairan Sungai Dua Laut cukup beragam. Hal ini
dibuktikan dengan konturnya yang semakin menurun atau curam pada saat menjauhi
pantai. Kedalaman di wilayah tenggara mencapai 7,5 meter sedangkan pada wilayah
selatan dan barat daya kedalaman berkisar 3 – 4 meter.
Gambar 10. Peta sebaran kedalaman Perairan
Sungai Dua Laut
Gambar
10 merupakan gambaran kontur kedalaman Perairan Sungai Dua Laut dalam bentuk 2
dimensi atau peta kontur. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa yang warna
biru muda memiliki kedalaman sebesar 0 – 1 meter sedangkan warna biru tua
merupakan daerah yang memiliki kedalaman sebesar 7 – 7,5 meter.
4.4.
Kelerengan
dan Geomorfologi Pantai
Kelerengan di
pesisir Sungai Dua Laut memiliki nilai yang beragam. Dari hasil penggabungan
antara data DEM dengan data hasil pengukuran topografi laut disajikan pada
Gambar 11 dibawah ini.
Gambar 11. Peta kelerengan Perairan Sungai Dua Laut
Berdasarkan
Gambar 11 nilai kelerangan minimum di wilayah ini berkisar antara 0 – 8% yang
ditandai dengan warna hijau. Untuk yang berwarna hijau muda merupakan
kelerengan yang memiliki nilai antara 8 – 15%. Wilayah yang berwarna kuning
memiliki nilai kelerengan sebesar 15 – 25%. Sedangkan wilayah yang berwarna
jingga memiliki nilai kelerengan antara 25 – 45%. Dan untuk wilayah yang
berwarna merah merupakan kelerengan maksimal di wilayah ini yakni berkisar
antara
45%.
Gambar 12. Geomorfologi pantai
Berdasarkan
Gambar 12 geomorfologi pantai di Perairan Sungai Dua Laut adalah landau dengan
karakteristik pantai berpasir. Pada saat terjadi surut terendah garis pantai
akan sangat jauh ke arah laut lepas sedangkan pada pasang tertinggi garis
pantai akan berada sangat dekat dengan vegetasi terakhir yang ada di daratan. Terdapat bekas aliran arus di sekitar muara sungai
saat terjadi surut terendah.
Gambar 11. Profil
pantai pada bagian barat, tengah dan timur
Berdasarkan Gambar
11 profil pantai pada bagian timur, barat dan tengah wilayah pantai Sungai Dua
Laut memiliki kelerengan yang landai. Hal ini dibuktikan dengan jarak 1,4,
jarak 1,6 dan jarak 1,8 km memiliki nilai kedalaman sebesar 3 meter.
Gambar 12. Lokasi pengambilan profil
pantai
Lokasi pengambilan
profil pantai terbagi menjadi tiga yaitu timur, barat dan tengah dengan jarak
antar lokasi sepanjang 1 km. Panjang penarikan dari garis pantai kelaut yaitu
sekitar 1,6 km hingga kedalaman 3 meter saat MSL.
DAFTAR
PUSTAKA
Arief,
M.,Winarso, G., dan Prayogo, T. 2011. Kajian Perubahan Garis Pantai Mengunakan
Data Satelit Landsat di Kabupaten Kendal. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh.
LAPAN. Jakarta Timur.
Baharuddin. 2017. Modul Oseanografi Fisik
Materi Pasang Surut. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Universitas Lambung
Mangkurat.
Maulana,
Fauzan. 2010. Sedimentasi laut. Ilmu kelautan, universitas padjajaran.














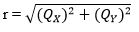







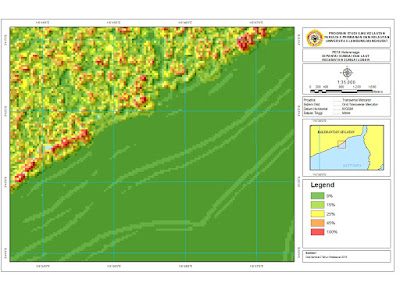



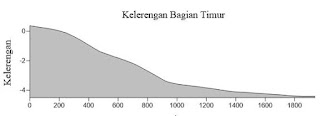

Komentar
Posting Komentar