PENANGANAN SIG TERHADAP PULAU-PULAU KECIL
TUGAS JURNAL MATA KULIAH SIG KELAUTAN
Linda Apriliani
1610716120003
PROGRAM STUDI ILMU
KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
BANJARBARU
2019
Abstrak
SIG merupakan suatu sistem yang didalamnya mencakup
informasi geografis untuk mengambarkan kondisi geografis sesuai dengan
kenyataan. pulau-pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas lebih
kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta ekosistemnya, minimnya basis data mengenai potensi pulau-pulau
kecil menjadikan SIG berperan dalam proses perolehan basis data. SIG diharapkan
mampu membantu mengenali potensi yang dimiliki sebuah pulau mampu terpetakan dengan
baik melalui data-data
spasial.
Kata kunci : SIG, pulau kecil, data, peta.
Pendahuluan
SIG (Sistem Informasi Geografis) pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun
1972 dengan nama Data Banks for
Develompment (Rais, 2005). Munculnya istilah Sistem Informasi Geografis
seperti sekarang ini setelah dicetuskan oleh General Assembly dari International
Geographical Union di Ottawa Kanada pada
tahun 1967.Dikembangkan oleh Roger Tomlinson, yang kemudian disebut CGIS
(Canadian GIS-SIG Kanada), digunakan untuk menyimpan, menganalisa dan mengolah
data yang dikumpulkan untuk inventarisasi Tanah Kanada (CLI-Canadian Land Inventory) sebuah
inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan
memetakan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas,
unggas dan penggunaan tanah pada skala 1:250000. Sejak saat itu Sistem Informasi Geografis berkembang di
beberapa benua terutama Benua Amerika, BenuaEropa, Benua Australia, dan
Benua Asia.
SIG merupakan suatu sistem yang didalamnya mencakup
informasi geografis untuk mengambarkan kondisi geografis sesuai dengan
kenyataan. Dengan bantuan sistem ini, kita mampu menggambarkan kenampakan yang
terlihat dilapangan agar dapat dituangkan kedalam bentuk 2 dimensi dalam hal
ini berupa peta. Atau dengan kata lain SIG adalah kumpulan yang terorganisasi
dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang
dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi,
menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Fungsi SIG sendiri sudah cukup beragam dalam kehidupan kita saat ini
salah satunya pengembangan wilayah pulau-pulau kecil.
Menurut UU RI No. 27 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa
pulau-pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km persegi beserta ekosistemnya. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan
kelautan di pulau-pulau kecil belum optimal dikarenakan ketidaktauan akan
potensi dari masing-masing pulau dan minimnya basis data mengenai potensi pulau-pulau kecil
yang ada menjadikan SIG berperan dalam proses perolehan basis data di Indonesia
sehingga hadirnya SIG diharapkan mampu membantu membuat potensi yang ada terpetakan dengan baik melalui data-data spasial.
Data spasial
mencakup dua komponen yaitu komponen spasial dan komponen tematik. Kedua
komponen tersebut saling terkait dan saling memperkuat informasi yang dikandung
dalam data tersebut. SIG mendasarkan pada kedua komponen tersebut dalam
berbagai analisis spasial yang dilakukan. Komponen spasial dan komponen tematik
dapat dianalisis secara bersama ataupun terpisah dari masing-masing komponen
tersebut. Komponen spasial dan tematik dapat diwujudkan menjadi sebuah
informasi spasial seperti peta-peta digital yang pada saat ini banyak digunakan
pada berbagai kepentingan.
Informasi geospasial yang ditampilkan tentunya tidak
hanya sekedar informasi letak dan koordinat namun disertakan pula informasi
penggunaan lahan, kondisi pasang surut, potensi perikanan, potensi tambang,
potensi penduduk, kebudayaan dan informasi lainnya. Penelitian yang dilakukan
Sarno (2013) mengenai inventarisasi pulau terluar dapat dikembangkan untuk pulau-pulau lainnya
di seluruh wilayah perairan Indonesia,
sehingga pemetaan pulau, identifikasi potensi sumberdaya pulau akan lebih mudah
diinventarisasikan dan mudah dalam perencanaan dan pengembangannya.
Kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi sumberdaya
pulau-pulau kecil merupakan salah satu upaya untuk menyediakan dan memberikan informasi
awal mengenai arah pemanfaatan pulau-pulau kecil yang rasional dan berkelanjutan, sebagaimana yang tertera di perundang-undangan. Tentunya
kajian lebih lanjut mengenai hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat sejauh
mana peranan SIG dalam pengembangan pulau-pulau kecil yang mendasari adanya
tulisan ini.
Metodologi Penelitian
A. Metode Perolehan Data
Menurut Baharuddin (2019)
menjelaskan bahwa perolehan data dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
1.
Identifikasi Potensi
Pengumpulan
data awal merupakan proses pengumpulan data pra-lapangan, meliputi perolehan data peta
dan citra satelit berikut pengolahannya, pengumpulan dan pengolahan data
kondisi awal lokasi, dan penetapan lokasi, jumlah dan metode sampling.
2.
Persiapan Peta dan Citra
Satelit
a.
Persiapan
Peta Dasar
Peta
dasar merupakan peta yang berisi informasi dasar kondisi wilayah,
meliputi batas poligon praktek, batas administratif, jalan dan sungai. Sesuai
dengan UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, peta dasar yang sesuai
digunakan dalam survei identifikasi potensi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
berupa Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 10.000, 1 : 25.000, 1 : 50.000 dan 1 :
100.000 yang dikeluarkan oleh BIG (Badan
Informasi Geospasial). Untuk meningkatkan kedetilan informasi pada peta dasar,
beberapa unsur/tema dasar dapat ditambahkan dari hasil delineasi melalui Google
Earth.
b.
Pengolahan
Citra Satelit
b. 1. Pengolahan
awal
Tahap
pengolahan awal citra satelit (image
preprocessing) dilakukan untuk memperbaiki data citra asli (raw data) menjadi citra satelit yang
siap untuk diinterpretasi. Pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan
kesalahan akibat hamburan partikel di atmosfer yang terekam oleh citra satelit
(radiometric correction), perbaikan
kesalahan posisi perekaman citra satelit terhadap referensi bumi (geometric correction) dan penajaman
obyek pada citra melalui perentangan nilai spektral citra.
-
Koreksi
Radiometrik
Koreksi radiometrik dilakukan untuk
menghilangkan kesalahan radiometrik, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh
adanya pantulan balik dari partikel-partikel di atmosfer yang ikut terekam oleh
detektor satelit, yang mengakibatkan terjadinya penambahan nilai piksel obyek
tertentu. Koreksi radiometrik dilakukan dengan cara memperbaiki nilai spektral
citra, yang pada prinsipnya adalah menghilangkan penambahan tingkat kecerahan
piksel akibat hamburan atmosfer.
Koreksi
geometrik yang paling mendasar adalah penempatan kembali posisi piksel
sedemikian rupa sehingga dihasilkan gambaran obyek yang sesuai dengan kondisi
sebenarnya di lapangan atau pada peta topografi. Pada koreksi geometrik terjadi
pengalihan posisi (relokasi) seluruh piksel pada citra sehingga membentuk
konfigurasi piksel baru yang dipersepsikan sebagai citra.
- Penajaman Citra
Penajaman
citra yang lazim digunakan ada dua, yakni ekualisasi histogram dan perentangan
linear. Teknik equalisasi histogram akan memberikan efek kontras yang tajam
(kontras maksimum) pada citra, sehingga perbedaan antara obyek yang satu dengan
obyek lainnya akan lebih jelas. Teknik ini lebih rumit dari perentangan linear
karena menggunakan hitungan statistik.
b.2 Interpretasi dan Delineasi
Interpretasi
citra satelit merupakan salah satu tahap identifikasi potensi pulau yang
dilakukan sebelum survei lapangan. Interpretasi citra satelit merupakan serangkaian kegiatan
identifikasi, pengukuran dan penterjemahan data-data dari data penginderaan
jauh untuk memperoleh informasi yang memiliki makna. Data
yang diperoleh melalui interpretasi citra antara lain penggunaan lahan, tutupan
mangrove dan terumbu karang.
Hasil
interpretasi penggunaan lahan, tutupan mangrove dan terumbu karang menghasilkan
peta tentatif yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan dicek di
lapangan. Hasil penentuan sampel bersama dengan informasi dasar lainnya digunakan
sebagai peta kerja untuk acuan ground
check.
-
Penggunaan
Lahan
Penggunaan lahan adalah aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan,
yang bersifat dinamis dan biasanya tidak tampak secara langsung dari citra
penginderaan jauh. Interpretasi penggunaan lahan pada citra penginderaan jauh
dilakukan dengan pendekatan 9 unsur interpretasi citra yaitu rona/warna,
bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi
bukti.
Interpretasi
citra untuk menghasilkan jenis-jenis penggunaan lahan pulau dilakukan dengan
cara digitasi on screen dengan
menggunaan software ArcGis. Klasifikasi
penggunaan lahan pulau harus mempertimbangkan hirarki pemetaan, misalnya citra
yang beresolusi sedang seperti Landsat akan menghasilkan kelas yang berbeda
dengan citra resolusi tinggi, seperti Ikonos dan Quickbird
3.
Pengumpulan dan pengolahan
data kondisi awal lokasi
Pengumpulan dan
pengolahan data awal lokasi dilakukan dengan pengumpulan bahan referensi dari
instansi terkait atau melalui internet. Hasil penelitian dan pendataan yang
pernah dilakukan oleh berbagai instansi dapat dijadikan referensi awal kondisi wilayah
dan sejauh mana kegiatan identifikasi potensi dan pemetaan pulau-pulau kecil
yang telah dilakukan. Data awal yang dikumpulkan diantaranya kondisi umum pulau,
status kawasan, kepemilikan pulau, iklim, oceanografi, genesis pulau, geologi
dan kerentanan bencana.
4.
Penetapan Lokasi, Jumlah dan
Metode Sampling
a. Penentuan Lokasi Sampel
Sampel lapangan untuk
uji interpretasi penggunaan lahan, mangrove dan obyek perairan dasar ditentukan
berdasarkan metode stratified
proporsional random sampling. Dengan menggunakan metode ini, unit terkecil
dalam penentuan sampel adalah hasil klasifikasi tiap jenis obyek pada setiap
peta. Sebagai contoh, unit terkecil pada peta penggunaan lahan adalah semak
atau permukiman.
b. Penentuan
Jumlah Sampel
Jumlah sampel diambil
secara proporsional sesuai dengan luas tiap kelas dari masing-masing tema peta
yaitu peta penggunaan lahan, peta obyek perairan dasar, dan peta mangrove.
c. Metode Pengamatan dan Pengukuran
Uji
hasil interpretasi penggunaan lahan dilakukan di setiap lokasi sampel dengan
cara pengamatan secara visual dan pencocokan antara hasil interpretasi citra
satelit dengan kondisi nyata di lapangan. Lokasi pengambilan sampel lapangan
harus sesuai dengan titik-titik sampel yang telah ditentukan sebelumnya.
Koordinat lokasi sampel di lapangan diukur dengan GPS.
4.
Survei Lapangan
Survei Lapangan (Ground Check), dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi kondisi wilayah,
meliputi kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk mengetahui
beberapa aspek tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah
mengumpulkan data dan informasi, baik primer maupun sekunder yang selanjutnya
akan diidentifikasi dan diklasifikasi.
B. Metode
Pengukuran
Beberapa aspek
yang diukur meliputi kondisi oseanografi fisik, oseanografi kimia dan kondisi
bio-ekologi. Parameter oseanografi fisik yang biasanya diamati adalah pasang surut, gelombang (pola, arah, tinggi), karakteristik
arus (pola, arah, kecepatan). Jika
data-data tersebut tidak dapat diamati secara langsung, maka akan digunakan
data sekunder dan peramalan. Beberapa parameter kualitas air diukur untuk
menentukan karakteristik dan kualitas perairan di lokasi studi meliputi suhu, DO, pH, kecerahan dan salinitas. Kondisi bioekosistem yang akan dimati adalah mangrove, lamun, ikan
(nekton), ikan karang, terumbu karang, plankton, substrat sedimen dan bentos.
Pengamatan ekosistem yang digunakan adalah metode-metode baku yang sudah teruji secara
ilmiah.
C.
Metode Analisis Data
1.
Verifikasi
dan Pengolahan Data Lapangan
Verifikasi data dilakukan untuk
mendapatkan data yang akurat dan valid. Verifikasi dilakukan melalui
pemeriksaan kesalahan pengambilan data, pemeriksaan kebenaran data tersebut di
lokasi pengambilan data, dan kejelasan sumber data. Pasca verifikasi,
pengolahan data dilakukan melalui tahapan inventarisasi data, kompilasi data,
klasifikasi data, penyamaan format data dan pengkorelasian data.
2.
Pengolahan
Data Tabular dan Tekstual
Data-data yang berbentuk
tabular/atribut dan tekstual (non spasial) yang dihasilkan dari pengolahan data
dapat secara langsung diolah dan dianalisis menggunakan program spreadsheet. Pengolahan data ini
menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam bentuk
deskripsi obyek atau lokasi, jumlah, persentase, frekuensi, informasi grafis
dalam bentuk gambar dan grafik, maupun informasi dalam bentuk data yang
terstruktur. Contoh data dalam bentuk tabular dan tekstual yaitu data sosial
ekonomi, data infrastruktur pulau, permasalahan dan peluang pengembangan,
dll.
3.
Reinterpretasi
Peta-Peta Tematik
Reinterpretasi merupakan tahap
perbaikan peta hasil interpretasi citra satelit dengan menggunakan hasil uji
lapangan. Proses perbaikan peta ini dilakukan dengan cara perbaikan batas-batas
polygon dari tiap kelas sesuai tema peta, diantaranya peta penggunaan lahan,
peta penutup lahan mangrove, dan peta obyek perairan dasar. Contoh
reinterpretasi adalah perbaikan poligon penggunaan lahan tanah terbuka yang
setelah di uji di lapangan berupa semak.
4.
Penyusunan
Peta-Peta Tematik
Penyusunan peta-peta
tematik dilakukan berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pengukuran
parameter kualitas perairan. Peta-peta tematik disusun untuk mengetahui sebaran
kondisi daya dukung pulau. Peta tematik yang diolah dan disusun meliputi peta oseanografi, peta
penggunan lahan, peta sebaran terumbu karang, padang lamun dan peta sebaran
tutupan mangrove.
5.
Analisis
Potensi Sumberdaya
Secara umum, pengolahan
dan analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi yang digunakan sebagai
input dalam penentuan seberapa besar potensi sumberdaya yang ada di pesisir,
laut dan pulau, meliputi informasi sumberdaya air tawar, terumbu karang, lamun
dan mangrove di wilayah studi. Informasi ini yang dijadikan dasar sejauh mana
potensi sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan.
Hasil
dan Pembahasan
Beberapa contoh
peranan SIG dalam pengembangan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut:
1. 1. Pengembangan Budidaya Laut (KJA dan
rumput laut)
Keramba jaring
tangkap dan Rumput Laut Keramba jaring tangkap merupakan salah satu cara
budidaya ikan di laut dan budidaya rumput laut banyak digemari oleh masyarakat
pesisir karena jika dikembangkan dengan optimal akan menghasilkan pendapatan
yang tinggi. Kedua budidaya tersebut memerlukan lokasi yang strategis, dengan
persyaratan yang sama menurut penelitian yang dilakukan Syofyan, dkk (2010) yaitu
klorofil, BOD, DO, kecerahan dan kedalaman.
Penelitian yang dilakukan Syofyan, dkk (2010) menunjukkan pemanfaatan
data penginderaan jauh dan SIG dalam penentuan lokasi untuk kesesuaian budidaya
keramba jaring tangkap dan rumput laut di Pulau Bunguran Kabupaten Natuna,
dengan perolehan dominansi kesesuaian kawasan untuk kegiatan keramba jaring tangkap
dan rumput laut berada pada kelas sesuai sebesar 49,4%, kemudian kelas sangat
sesuai sebesar 31,1% dan tidak sesuai sebesar 19,5%. Dengan gambar spasialnya
sebagai berikut:
Gambar 1. Peta Kelas Kesesuaian
Kawasan Keramba Jaring Tancap dan Rumput Laut di Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna (Syofyan, dkk, 2010)
2. 2. Monitoring
Ekosistem Pesisir dan Laut
·
Ekosistem Lamun
Penelitian
ini dilakukan oleh Supriyadi (2008) di Teluk Kotania dan Pelitajaya Kabupaten
Seram Bagian Barat- Maluku Tengah. Parameter yang diambil saat pengukuran ialah
pola arus air pasang surut, arus permukaan, pola sebaran sedimen, kondisi suhu
dan salinitas. Metode yang digunakan ialah melalui interpretasi data citra
satelit ASTER hasil rekaman 17 September 2005 dan posisi titik sampling
(Lintang dan Bujur) ditentukan dengan menggunakan GPS (Global Position System)
yang telah disesuaikan dengan datum WGS84.
Persentase
tutupan lamun (seagrass cover) ekosistem lamun di perairan Teluk Pelitajaya dan
Kotania secara umum relatif tinggi antara 10-95 % dan hampir merata di seluruh
perairan Teluk (Gambar3). Nilai persentase tutupan lamun dapat mencerminkan
besar kecilnya kandungan biomasa lamun (Kuriandewa, komunikasi pribadi).
Persentase tutupan lamun di atas 75 % tersebar merata di perairan dangkal Teluk
Kotania khususnya di bagian luar (open sea), sedangkan persentase tutupan
rendah cenderung berada di teluk yang menjorok ke dalam.
Gambar 2. Sebaran persentase
tutupan lamun
3. 3. Analisis Kelayakan Zona Inti
Penelitian
ini dilakukan oleh Miftahudin dkk (2017) di Perairan Kepulauan Selat Nasik,
yang merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Perairan (KKP) wilayah
administrasi kabupaten Belitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode observasi. Observasi dilakukan dengan 2 cara yaitu FGD (Focused Discussion Group) atau wawancara
dan pengukuran lapangan. FGD atau wawancara dilakukan untuk mendapatkan
lokasi
usulan zona inti secara garis besar berdasarkan persepsi masyarakat melalui
pendekatan pemetaan partisipatif. Setelah melewati proses analisis maka hasil
penilaian terhadap kesesuaian zona inti tampil dalam bentuk layout peta
kesesuaian.
Gambar
3. Peta Kesesuaian di Pulau Piling
4. 4. Pengembangan Wisata Bahari
Wisata
Bahari Pemanfaatan potensi pesisir dan lautan lainnya adalah pemanfaatan dalam
bidang wisata, pemanfaatan ini agaknya
mulai banyak disadari oleh masyarakat Indonesia, yang mulai berlomba-lomba
dalam melakukan marketing wisata bagi wilayah pesisirnya, namun perlu dicermati
kesesuaiannya agar terjadi keberlanjutan bagi pengembangan wisata nantinya,
Pemanfaatan
teknologi Penginderaan Jauh dan SIG untuk penentuan lokasi pariwisata bahari
telah dilakukan Winarso, dkk (2014) dengan parameter lingkungan yang dideteksi
dari penginderaan jauh antara lain kecerahan, terumbu karang, dan kedalaman.
Kemudian dengan SIG ditentukan lokasi yang sesuai untuk wisata bahari seperti
diving dan snorkeling.
Gambar
4. Lokasi rekomendasi untuk pariwisata bahari di NTB berdasarkan data penginderaan jauh (Winarso, dkk, 2014)
Kesimpulan
Kesimpulan
dari beberapa uraian diatas ialah peranan SIG dalam pengembangan pulau-pulau
kecil adalah membangun basis data yang selama ini belum ada dan potensi yang belum
terpetakan dengan baik sehingga arah pembangunan di pulau-pulau kecil masih
terkendala. Melalui SIG diharapkan potensi pulau-pulau kecil dapat terlihat
sehingga pembangunan dapat dilakukan lebih optimal.
Daftar
Pustaka
Baharuddin. 2018. Bahan Ajar Pemetaan
Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil. Progam
Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Lambung
Mangkurat.
Harahap dan Yanuarsyah. (2012). Aplikasi
Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Zonasi Jalur Penangkapan Ikan di
Perairan Kalimantan Barat. Jurnal Akuatika. Vol. III No. 1/ Maret 2012.
Shalihati. 2014. Pemanfaatan Penginderaan
Jauh Dan Sistem Informasi Geografi Dalam Pembangunan Sektor Kelautan Serta Pengembangan Sistem Pertahanan Negara
Maritim. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Supriyadi I. 2008. Pemetaan Kondisi
Ekosistem Lamun Dan Biota Asosiasi Di Teluk Kotania Dan Pelitajaya Kabupaten
Seram Bagian Barat- Maluku Tengah. LIPI Jakarta.
Syofyan, I., Rommie Jhonerie, Yusni Ikhwan
Siregar. (2010). Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penentuan Kesesuaian
Kawasan Keramba Jaring Tancap dan Rumput Laut Di Perairan Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna. Jurnal Perikanan dan Kelautan. halaman 111-120.
Winarso, G., dkk (2014). Aplikasi
Penginderaan Jauh untuk Mendukung Program Kemaritiman. Publikasi ilmiah.




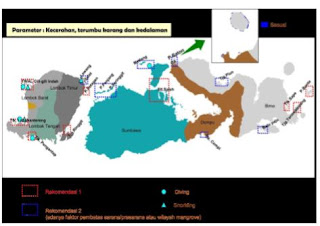
Komentar
Posting Komentar